Oleh LAKSAMANA SUKARDI

MEMASUKI tahun 1990, usia saya 33 tahun. Saya bersyukur karena di usia tersebut telah mencapai karier sebagai eksekutif puncak di Perbankan, dengan gaji dan fasilitas yang lumayan tinggi untuk pemuda seumur saya pada waktu itu. Tapi, pencapaian karier yang relatif cepat dalam usia yang masih muda, juga membuat saya bergulat dengan serangkaian pertanyaan yang tertuju pada diri sendiri: apakah saya akan menghabiskan usia saya untuk terus berkarier di dunia perbankan? Apakah saya harus berhenti atau pindah karier ke bidang lain? Jika saya bekerja sampai pensiun, bukankah itu berarti 30 tahun ke depan saya hanya akan berkutat dengan masalah perbankan? Lantas apa yang akan saya peroleh selain materi? Apakah ilmu saya akan bertambah? Apakah dunia perbankan akan berubah?
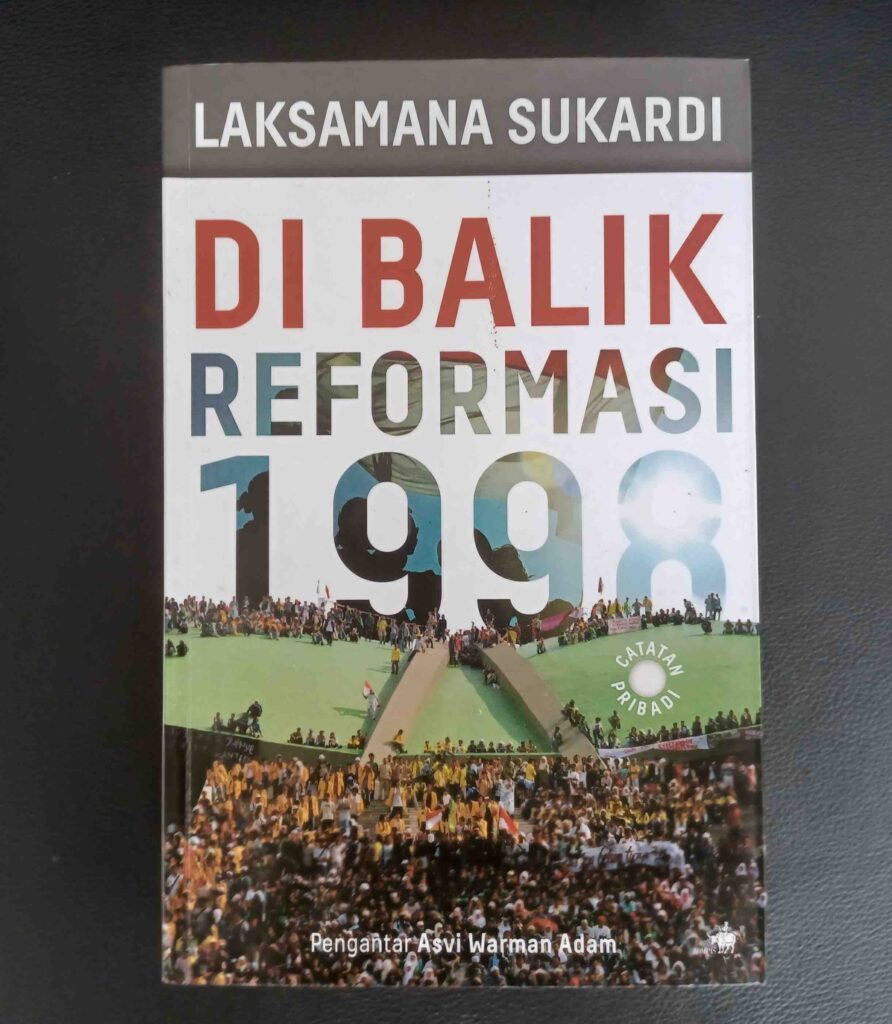
Pergulatan dengan serangkaian pertanyaan tersebut, bukan karena saya tidak menghargai rejeki (gaji dan fasilitas yang sedang saya nikmati), atau menampik nasib baik yang diberikan Tuhan, melainkan timbul akibat situasi dan kondisi serta naluri saya yang telah terbiasa untuk selalu bertanya dalam menapak setiap kondisi kehidupan. Barangkali pula hal itu terjadi karena saya terlahir sebagai anak wartawan. Ayah saya, Gandhi Sukardi, adalah wartawan Kantor Berita Antara yang hingga akhir hayatnya tetap aktif menulis. Kakek saya, Didi Sukardi, adalah salah satu pahlawan Perintis Pers Nasional. Adik kandung saya, Wina Armada Sukardi, sampai sekarang juga menekuni profesi wartawan. Tentu saja terlahir sebagai anak wartawan, tumbuh dewasa dalam keluarga wartawan, membuat saya terlatih dan terbiasa bertanya, sehingga dengan demikian terdidik untuk berpikir merdeka. Sehingga dapat pula dikatakan saya lahir dan bertumbuh dalam tradisi membaca, menulis dan bernalar kritis serta mengedepankan obyektivitas.
Oleh karena itu, saya memiliki kebiasaan untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu pada diri sendiri, apalagi ketika harus mengambil keputusan yang sangat penting. Saya juga selalu bertanya mengenai sebab dan akibat dari sebuah keadaan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang harus dicerna dengan nalar saya sendiri. Saya selalu bertanya, karena bagi saya bertanya adalah sebuah upaya untuk melatih dan merawat kebiasaan bernalar kritis dan berpikir merdeka.

Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Gusti Allah, yang telah memberikan jalan tol untuk meniti karier profesional sebagai seorang bankir. Tanpa kehendakNya, mustahil saya bisa memulai karier di sebuah bank multinasional. Saya diterima sebagai Executive Trainee di Citibank, sebuah bank terbesar dari Amerika. Padahal, saya tidak pernah sekolah di Amerika atau di luar negeri dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan ataupun di bidang ekonomi. Ibaratnya, kalau ada prakualifikasi, mestinya saya tidak akan diterima bekerja di bank Internasional seperti Citibank yang pada waktu itu bertengger sebagai bank peringkat nomor satu di dunia.
Modal saya pada waktu itu hanyalah sebuah kebanggaan titel sarjana yang sama dengan Presiden Soekarno, yaitu jebolan fakultas teknik sipil Institut Teknologi Bandung. Saya selalu bangga karena mengalami belajar dalam ruang kuliah yang sama dengan Bung Karno, bahkan duduk di bangku yang pernah diduduki oleh Bung Karno ketika menjadi mahasiswa di sana. Itulah modal dan kebanggaan saya satu-satunya pada waktu itu. Kebanggaan yang meniupkan semangat untuk “meniru’ dan mengikuti jejak Bung Karno. Beliau memberikan inspirasi kepada saya sebuah kemerdekaan dan kesempatan untuk belajar, serta berjuang menjawab tantangan untuk mengisi kemerdekaan tersebut.
Tentu saja pada waktu itu, sekali lagi, saya sungguh bersyukur, alhamdulillah, karena telah diberikan berkah sebuah nasib kehidupan ekonomi yang sangat baik. Terutama jika dibandingkan dengan teman teman pemuda sebaya saya pada waktu itu, khususnya teman teman kuliah seangkatan di Institut Teknologi Bandung. Karier saya melesat dengan cepat untuk pemuda seumur saya. Sehingga saya menikmati kehidupan ekonomi yang sangat baik. Saya memiliki rumah di daerah elite Kebayoran Baru, punya kendaraan mewah dan fasilitas fasilitas bergengsi lainnya.

Kembali kepada pergulatan dengan serangkaian pertanyaan di atas, jawaban yang normal tentunya adalah: terus menikmati karier perbankan dengan segala kenikmatan fasilitas sebagai top eksekutif. Namun demikian, anehnya, jawaban normal itu justru menimbulkan pertanyaan: apakah saya harus menghabiskan sisa karier saya yang masih panjang, sebagai seorang bankir? Bagaimana masa depan perbankan Indonesia? Pertanyaan tersebut muncul terutama karena ketika menjadi bankir, saya harus berhadapan dan menyaksikan sejumlah kenyataan yang perih dan memuakkan, yang membuat akal pikiran dan nurani saya terluka. * (Bersambung: Parasit Ekonomi Indonesia)









